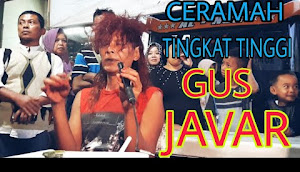Gambar.
Ruben Cornelius Siagian sedang memaparkan Gagasanya
Kabar Nusantara - Medan, 11 Agustus 2025 — Rasa kecewa dan kegelisahan kini menyelimuti banyak peneliti di tanah air. Di balik prestasi akademik yang kerap dibanggakan di forum internasional, masih ada kenyataan pahit yang jarang diungkap yaitu lemahnya kualitas pengelolaan jurnal ilmiah di Indonesia. Kondisi ini disoroti langsung oleh akademisi sekaligus peneliti independen, Ruben Cornelius Siagian, yang menyebut bahwa sistem publikasi nasional sedang berada dalam “zona bahaya” jika pemerintah tidak segera melakukan pembenahan total.
Bagi Ruben, masalah ini bukan
sekadar statistik atau keluhan sepele di media sosial. “Dampaknya nyata,
langsung menggerus produktivitas riset kita,” ujarnya dengan nada prihatin. Ia
menegaskan bahwa ribuan peneliti terjebak dalam proses editorial yang lambat,
tidak transparan, dan kerap berujung penolakan tanpa penjelasan memadai.
Ironisnya, di tengah
stagnasi ini, perhatian pemerintah tampaknya lebih tersita pada kegiatan
seremonial yang gemar menampilkan barisan rapi, parade militer, dan jargon
ketahanan ala masa lalu ketimbang memastikan ekosistem riset dan publikasi
berjalan sehat. “Kalau lomba baris-berbaris, kita mungkin juara dunia. Tapi
untuk urusan mutu publikasi ilmiah? Kita seperti negara yang rela tertinggal,
asalkan barisannya rapat,” sindir Ruben. Ia membandingkan situasi ini dengan
masa BJ Habibie, di mana pemerintah justru menempatkan riset dan inovasi
sebagai urat nadi pembangunan bangsa. Di era itu, peneliti diberi ruang,
dukungan, dan kebanggaan nasional untuk berkompetisi di panggung dunia, bukan
sekadar menjadi penonton parade di lapangan. “Dulu, visi teknokrat memacu kita
membuat pesawat, kapal, dan teknologi strategis. Sekarang, visi yang terlihat
hanya memacu derap langkah pasukan,” ucap Ruben.
Perbandingan ini
semakin ironis jika melihat alokasi anggaran negara. Berdasarkan data RAPBN
2025, Kementerian Pertahanan memperoleh anggaran fantastis sebesar Rp165,2
triliun, menjadikannya penerima dana terbesar di antara semua kementerian.
Sebaliknya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang
memikul beban pembinaan riset dan publikasi ilmiah hanya mendapat Rp83,2
triliun, kurang dari setengah anggaran pertahanan. Sementara itu, Kepolisian RI
memperoleh Rp126 triliun, bahkan lebih besar daripada total dana untuk seluruh
kegiatan pendidikan dan riset nasional. Ruben menilai angka ini bukan sekadar
statistik anggaran, tetapi cermin dari prioritas politik negara. “Kita
menggelontorkan ratusan triliun untuk senjata, seragam, dan parade, tapi untuk
riset yang bisa mengubah masa depan, kita hanya memberi setengahnya. Ini
seperti membangun benteng megah di tengah kota yang sekarat kelaparan,”
ujarnya. Nuansa militeristik yang kian kental di era Prabowo, lanjutnya,
membuat iklim akademik semakin terpinggirkan, seolah pengetahuan dan data tidak
sepenting disiplin ala kasau lapangan. Ruben menegaskan, jika kondisi ini terus
dibiarkan, Indonesia bukan hanya tertinggal dalam peringkat publikasi, tetapi
juga kehilangan momentum strategis untuk menjadi pemain utama di kancah ilmu
pengetahuan. Dan, tambahnya dengan nada sinis, “Mungkin saat itu pemerintah
akan bangga karena jumlah parade militernya meningkat, walau jumlah publikasi
dan sitasi ilmiahnya tetap memprihatinkan.”
Ruben Cornelius
Siagian mengisahkan sebuah banyak pengalaman yang begitu menyesakkan hati,
salah satu contoh datang dari seorang peneliti dari berbagai daerah. Peneliti
ini, dengan segala keterbatasan fasilitas di daerahnya, telah mencurahkan dua
tahun penuh untuk menuntaskan sebuah riset strategis. Bukan hanya waktu, tetapi
juga dana pribadi yang tak sedikit bahwa lebih dari tiga puluh juta rupiah ia
habiskan demi memastikan penelitiannya memiliki kualitas dan relevansi tinggi.
Harapannya sederhana, namun sangat menentukan masa depannya yaitu publikasi
tepat waktu di sebuah jurnal nasional terakreditasi, agar bisa memenuhi syarat
administratif untuk mendaftar beasiswa doktoral di luar negeri. Namun,
kenyataan yang menantinya justru jauh dari harapan. Setelah naskah dikirim,
bulan demi bulan berlalu tanpa ada satu pun kabar dari pihak jurnal. Empat
belas bulan lamanya ia menunggu, menahan cemas, bahkan menolak beberapa
kesempatan riset lain demi fokus pada proses publikasi yang tak kunjung
selesai. Hingga akhirnya, sebuah email singkat datang. Isinya penolakan. Tak
ada penjelasan mendalam, tak ada peer review yang memadai dan hanya satu
kalimat alasan yang dingin yaitu “Tidak sesuai fokus jurnal.”
Bagi Ruben, inilah
salah satu potret paling menyedihkan dari sistem publikasi ilmiah di Indonesia.
Yang membuat kisah ini semakin tragis adalah konteks penelitian tersebut. Saat
itu, topiknya sangat relevan dengan kebijakan pemerintah yang sedang hangat dibahas.
Temuan-temuannya berpotensi memberi kontribusi nyata bagi pengambilan keputusan
di tingkat nasional. Namun, karena publikasi gagal, riset itu kehilangan
momentum. Saat peneliti mencoba mengajukan kembali ke jurnal lain, datanya
sudah dianggap kadaluarsa dan tak lagi menarik bagi pembaca maupun pembuat
kebijakan.
Kesempatan beasiswa yang menjadi cita-citanya sejak lama pun sirna begitu saja. “Ini bukan sekadar penolakan akademik. Ini memutus jalan masa depan seseorang. Kerja keras bertahun-tahun, pengorbanan finansial, dan idealisme yang ia bawa pulang dari kampungnya dan semuanya runtuh hanya karena sistem jurnal yang tidak berjalan semestinya,” ujar Ruben dalam menceritakan kisah temanya, dengan nada getir.
Rasa prihatin Ruben Cornelius
Siagian semakin beralasan ketika menelaah data publikasi internasional yang
dirilis oleh Scopus pada tahun 2020. Angka-angka tersebut, menurutnya, bukan
sekadar statistik kering, melainkan cermin nyata dari ketertinggalan bangsa
dalam persaingan ilmu pengetahuan global. Indonesia, dengan populasi lebih dari
270 juta jiwa, hanya mampu mencatat 49.160 publikasi ilmiah, atau jika dihitung
per kapita, setara dengan 181 artikel untuk setiap satu juta penduduk.
Perbandingan ini terasa memukul ketika disejajarkan dengan Australia, yang
mampu menghasilkan 4.109 artikel per juta penduduk, dan Kanada dengan 3.184
artikel per juta penduduk bahwa dua negara yang jumlah penelitinya jauh lebih
sedikit, namun efisiensi dan dampaknya berlipat ganda.
Lebih memilukan lagi
adalah fakta mengenai rata-rata sitasi per artikel. Penelitian dari Indonesia
hanya mengantongi rata-rata 18,3 sitasi, angka yang tidak hanya lebih rendah
dari Australia atau Kanada, tetapi bahkan tertinggal dari negara tetangga seperti
Malaysia dan Singapura. Padahal, kedua negara tersebut memiliki jumlah
publikasi yang lebih sedikit dibanding Indonesia. “Ini menunjukkan bahwa
persoalan kita bukan hanya pada kuantitas, tetapi juga kualitas dan relevansi
riset yang dihasilkan,” ujar Ruben dengan nada prihatin.
Ia menegaskan bahwa
di balik angka-angka tersebut tersimpan persoalan mendasar dalam ekosistem
publikasi ilmiah di tanah air. Banyak peneliti yang sudah menghasilkan karya
berkualitas, namun terhambat oleh sistem publikasi yang lamban, kurang
transparan, dan kerap tidak ramah terhadap penulis. “Jumlah peneliti kita
besar, tapi dampaknya kecil. Salah satu biang keladinya adalah proses publikasi
yang tidak ramah peneliti. Bayangkan, ide dan temuan yang seharusnya segera
dibaca dunia malah tertahan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun,” tambahnya.
Ruben menilai, jika
kondisi ini terus dibiarkan, Indonesia bukan hanya akan tertinggal dalam
peringkat publikasi, tetapi juga kehilangan momentum strategis untuk menjadi
pemain utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan di kawasan. Data ini,
menurutnya, seharusnya menjadi alarm nasional bagi pemerintah, perguruan
tinggi, dan lembaga penelitian untuk segera berbenah, bukan sekadar demi
mengejar angka, melainkan demi mengangkat martabat dan daya saing bangsa di
panggung global.
Ruben Cornelius
Siagian mengungkapkan bahwa masalah rendahnya kualitas jurnal ilmiah di
Indonesia bukanlah persoalan yang muncul tiba-tiba, melainkan sudah mengakar
selama bertahun-tahun tanpa solusi yang memadai. Menurutnya, manajemen
editorial di banyak jurnal belum dikelola secara profesional. Alur peer review
kerap tidak jelas, membuat penulis bingung harus menunggu berapa lama atau
tahapan apa saja yang sedang berlangsung. Akibatnya, proses yang seharusnya
bisa selesai dalam hitungan bulan justru berlarut hingga lebih dari setahun.
Kondisi ini semakin
diperburuk oleh minimnya pelatihan khusus bagi para editor dan reviewer. Banyak
di antara mereka belum menguasai standar internasional seperti COPE atau sistem
penilaian Scopus, sehingga kualitas telaah terhadap naskah sering kali rendah
dan tidak konstruktif. Penulis kerap menerima komentar yang terlalu singkat,
umum, bahkan terkadang tidak relevan dengan topik penelitian. Situasi ini
menimbulkan kesan bahwa proses penilaian hanya formalitas, bukan upaya serius
untuk meningkatkan mutu karya ilmiah. Selain itu, Ruben menyoroti bahwa
teknologi pengelolaan naskah di banyak jurnal Indonesia masih tertinggal jauh
dibandingkan negara lain. Banyak jurnal yang masih mengandalkan sistem manual
atau email biasa untuk mengirim dan menerima naskah, alih-alih menggunakan
platform manajemen digital yang terintegrasi. Hal ini membuat komunikasi antara
penulis, editor, dan reviewer menjadi lambat, penuh risiko kehilangan data, dan
rawan miskomunikasi.
Lebih jauh, ia
menegaskan bahwa ketiadaan batas waktu yang tegas untuk proses publikasi
membuat para penulis terombang-ambing tanpa kepastian. Beberapa bahkan mengaku
menunggu hingga 18 bulan hanya untuk mendapatkan kabar awal dari redaksi.
Ketika akhirnya naskah mereka ditolak, alasan yang diberikan sering kali tidak
transparan atau terlalu umum, seperti “tidak sesuai fokus jurnal,” tanpa
penjelasan rinci.
“Kalau kondisi ini
terus dibiarkan,” ujar Ruben dengan nada tegas, “riset kita akan terus kalah
bersaing. Indonesia hanya akan menjadi konsumen pengetahuan dari luar negeri,
sementara potensi ilmuwan kita tidak pernah benar-benar terwujud di panggung
global.”
Ruben Cornelius
Siagian menegaskan bahwa perbaikan mutu jurnal ilmiah di Indonesia tidak dapat
lagi menunggu. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah strategis dan
terukur dengan membentuk sebuah Badan Nasional Standar Jurnal Ilmiah yang
memiliki kewenangan penuh untuk mengawasi kualitas editorial, memastikan proses
publikasi berjalan sesuai standar internasional, serta memberikan sanksi kepada
pengelola jurnal yang tidak profesional. Lembaga ini, kata Ruben, harus
berfungsi seperti “otoritas pengawas” yang mampu mengawal integritas ilmiah
dari hulu ke hilir.
Selain itu, Ruben
menilai peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci. Ia mendorong
adanya pelatihan rutin bagi editor dan reviewer yang disusun berdasarkan
standar etik dan mutu publikasi global seperti COPE, Scopus, dan DOAJ.
Pelatihan ini diharapkan tidak hanya membekali mereka dengan keterampilan
teknis penilaian naskah, tetapi juga membentuk sikap profesional dalam menjaga
komunikasi yang transparan dan menghargai waktu para penulis.
Tak kalah penting, Ruben juga menyoroti perlunya platform manajemen naskah digital yang modern dan transparan. Sistem ini harus dilengkapi dengan fitur tracking system yang memungkinkan penulis memantau perkembangan naskah mereka secara *real-time*, mulai dari tahap penerimaan, proses review, hingga keputusan akhir. Dengan cara ini, tidak akan ada lagi penulis yang “dihilangkan” kabarnya selama berbulan-bulan tanpa kejelasan.
Untuk mendorong kinerja yang lebih baik, Ruben mengusulkan adanya insentif finansial dan penghargaan khusus bagi jurnal yang mampu bekerja cepat, transparan, dan menghasilkan publikasi berkualitas tinggi. Menurutnya, sistem penghargaan akan memicu persaingan sehat antarjurnal, sehingga mutu keseluruhan publikasi nasional meningkat secara signifikan.
Sebagai penutup, Ruben
menggarisbawahi pentingnya menetapkan batas waktu maksimal tiga hingga empat
bulan bagi seluruh proses peninjauan hingga keputusan akhir publikasi. Batas
ini, tegasnya, bukan hanya realistis, tetapi juga merupakan standar umum di banyak
negara maju. “Ilmu pengetahuan adalah aset strategis bangsa. Kalau kita gagal
mengelola publikasi, sama saja kita menghambat kemajuan kita sendiri,”
pungkasnya dengan nada serius.