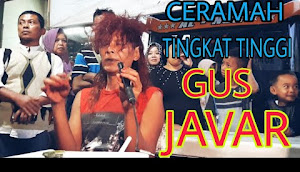Oleh: [Arinda Rahmatuzzahro]
202310180311079
Kabar Nusantara - Pembangunan ekonomi Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan selama dua dekade terakhir. Indikator makroekonomi menunjukkan pertumbuhan yang stabil, investasi meningkat, dan tingkat kemiskinan menurun. Di balik angka-angka tersebut, terdapat persoalan mendasar yang terus membayangi: ketimpangan struktural yang melebar, dominasi kapital besar, serta lemahnya pemerataan kesejahteraan di tingkat akar rumput. Pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi pertumbuhan yang tidak disertai pemerataan hanya akan melahirkan kemajuan semu.
Persoalan arah pembangunan ekonomi Indonesia sejatinya bukan sekadar masalah teknis, melainkan masalah paradigma. Selama ini, pembangunan cenderung berorientasi pada pertumbuhan (growth-oriented development) yang diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB). Teori pertumbuhan klasik seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo menekankan pentingnya akumulasi modal dan efisiensi pasar. Namun, dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, pendekatan tersebut sering kali gagal menciptakan keadilan ekonomi karena mengabaikan faktor sosial, kelembagaan, dan distribusi sumber daya.
Model pembangunan yang terlalu bergantung pada pasar bebas telah menciptakan fenomena yang disebut “growth without equity” pertumbuhan tanpa pemerataan. Sektor industri besar dan investasi asing mendominasi perekonomian, sementara sektor informal dan usaha mikro justru menjadi tumpuan sebagian besar masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, sekitar 60% tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal dengan tingkat upah rendah. Meskipun ekonomi tumbuh, kesejahteraan riil masyarakat belum meningkat secara proporsional.
Orientasi pembangunan yang terlalu menekankan pada proyek infrastruktur besar dan industrialisasi skala tinggi patut dikritisi. Infrastruktur memang penting, tetapi ketika tidak diimbangi dengan pemberdayaan ekonomi lokal, dampaknya hanya menguntungkan pelaku usaha besar. Di banyak daerah, proyek strategis nasional justru menimbulkan eksklusi sosial, konflik lahan, dan marjinalisasi masyarakat kecil.
Arah pembangunan kita masih lemah dalam aspek inovasi dan produktivitas sektor riil. Indonesia belum sepenuhnya keluar dari jebakan ekonomi berbasis komoditas (commodity trap). Ketergantungan pada ekspor bahan mentah seperti nikel, batu bara, dan kelapa sawit menunjukkan bahwa transformasi menuju industri berbasis nilai tambah masih jauh dari harapan. Padahal teori pembangunan strukturalis seperti yang dikemukakan oleh Raul Prebisch menegaskan bahwa ketergantungan pada ekspor primer akan membuat negara berkembang terus berada dalam posisi subordinat terhadap negara industri maju.
Secara empiris, ketimpangan ekonomi Indonesia masih tinggi. Koefisien Gini per September 2024 tercatat 0,382 memang turun dibanding satu dekade lalu, tetapi masih menunjukkan kesenjangan yang nyata. Sebagian besar kekayaan nasional dikuasai oleh kelompok atas. Laporan Credit Suisse (2023) mencatat bahwa 1% penduduk terkaya Indonesia menguasai lebih dari 45% total kekayaan nasional.
Disparitas wilayah masih menjadi tantangan klasik. Pembangunan ekonomi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yang menyumbang sekitar 58% terhadap PDB nasional. Sementara kawasan timur Indonesia tertinggal jauh, baik dari segi infrastruktur, produktivitas, maupun akses pendidikan dan teknologi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembangunan belum berjalan inklusif, padahal konsep ekonomi kerakyatan dan pemerataan wilayah sudah lama menjadi semangat dalam konstitusi.
Masa depan pembangunan ekonomi Indonesia perlu diarahkan pada transformasi yang lebih mendasar. Paradigma pertumbuhan ekonomi inklusif (inclusive growth) harus menjadi orientasi utama. Artinya, pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya PDB, tetapi dari seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat kecil, petani, nelayan, pekerja informal, dan pelaku UMKM.
Pertama, negara perlu memperkuat ekonomi berbasis nilai tambah (value-based economy). Indonesia memiliki potensi besar dalam sumber daya alam, namun nilai ekonominya akan berlipat jika didukung oleh teknologi, riset, dan inovasi. Pemerintah harus mempercepat transformasi industri melalui kebijakan hilirisasi yang tidak hanya berorientasi pada ekspor bahan mentah, tetapi pada penciptaan ekosistem industri domestik yang kuat, berkelanjutan, dan adil.
Kedua, pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal perlu menjadi prioritas strategis, bukan sekadar pelengkap. Berdasarkan data Kemenkop UKM (2024), UMKM menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional, tetapi hanya berkontribusi sekitar 60% terhadap PDB. Ini menunjukkan perlunya kebijakan afirmatif dalam bentuk akses permodalan, digitalisasi, dan perlindungan pasar bagi usaha kecil agar dapat naik kelas dan menjadi bagian dari rantai nilai global.
Ketiga, arah pembangunan masa depan harus menempatkan pemerataan wilayah dan keadilan sosial sebagai fondasi utama. Konsep ekonomi Pancasila, yang menekankan keseimbangan antara efisiensi pasar dan keadilan sosial, relevan untuk dihidupkan kembali. Negara tidak boleh sekadar menjadi regulator, tetapi harus berperan aktif sebagai penggerak pembangunan yang berpihak pada kelompok rentan dan daerah tertinggal.
Teori-teori pembangunan modern seperti endogenous growth theory menegaskan bahwa sumber utama kemajuan ekonomi bukan lagi akumulasi modal, melainkan pengetahuan, inovasi, dan kualitas manusia. Dalam konteks ini, investasi pada pendidikan, riset, dan teknologi digital menjadi prasyarat utama. Pembangunan ekonomi abad ke-21 tidak dapat lagi mengandalkan eksploitasi sumber daya alam, melainkan transformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy).
Masa depan ekonomi Indonesia akan sangat ditentukan oleh keberanian mengambil langkah reformasi struktural yang berorientasi jangka panjang. Pertumbuhan yang berkeadilan tidak lahir dari kebijakan yang populis, melainkan dari sistem ekonomi yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.
Pembangunan sejati bukan hanya tentang seberapa cepat ekonomi tumbuh, tetapi seberapa adil manfaatnya dibagi. Indonesia membutuhkan arah baru dari pembangunan yang mengejar angka, menuju pembangunan yang memuliakan manusia.